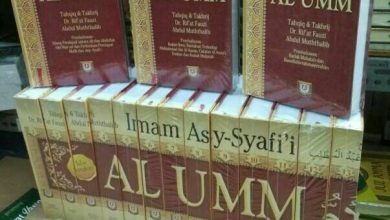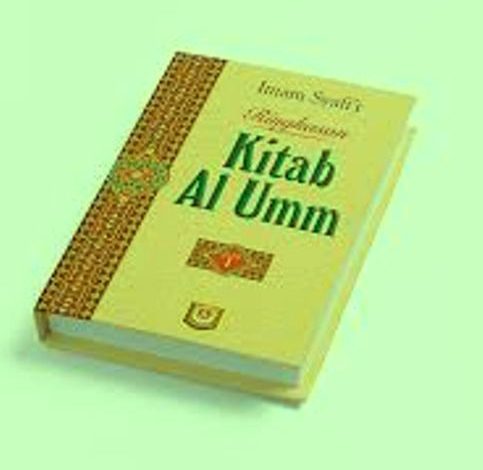
[BAB TENTANG PENAHANAN ORANG YANG PAILIT]
(Imam Syafi’i -rahimahullah Ta’ala- berkata): Jika seseorang memiliki harta yang terlihat di tangannya dan tampak darinya sesuatu, kemudian para pemilik hutang menuntutnya dan membuktikan hak-hak mereka, maka jika dia mengeluarkan harta atau ditemukan hartanya yang tampak yang mencukupi untuk membayar hutang-hak mereka, mereka diberikan hak-hak mereka, dan dia tidak ditahan. Namun jika tidak tampak hartanya dan tidak ditemukan sesuatu yang mencukupi untuk membayar hak-hak mereka, maka dia ditahan dan dijual hartanya sebanyak yang bisa didapatkan. Jika dia mengaku butuh, maka dia diminta mendatangkan bukti atas kebutuhannya, dan diterima darinya bukti tentang kebutuhan dan bahwa dia tidak memiliki apa-apa jika mereka adalah orang-orang yang adil dan mengenalnya sebelum penahanan. Aku tidak akan menahannya, dan pada hari aku menahannya serta setelah beberapa waktu dia habiskan dalam penahanan, aku juga akan menyumpahnya dengan nama Allah bahwa dia tidak memiliki apa-apa dan tidak menemukan cara untuk membayar krediturnya, baik dengan uang tunai, barang, atau cara apa pun. Kemudian aku akan membebaskannya dan melarang krediturnya untuk menekannya setelah dibebaskan. Aku tidak akan mengembalikannya ke penahanan sampai mereka membawa bukti bahwa dia telah mendapatkan harta. Jika mereka membawa bukti bahwa terlihat harta di tangannya, aku akan menanyakannya. Jika dia mengatakan itu harta mudharabah yang belum aku kelola atau sudah aku kelola tetapi belum menghasilkan atau tidak ada kelebihan untukku, maka aku akan menerima alasannya dan menyumpahnya jika mereka menghendaki. Jika dia mengingkari, aku juga akan menahannya sampai dia membawa bukti seperti pertama kali dan menyumpahnya seperti sebelumnya. Aku tidak akan menyumpahnya dalam salah satu dari dua penahanan sampai dia membawa bukti, dan aku akan bertanya tentangnya kepada orang yang mengenalnya untuk memberitahukan kebutuhannya. Tidak ada batas waktu penahanan selain untuk mengungkap keadaannya. Jika hakim telah yakin dengan apa yang kujelaskan, maka tidak boleh menahannya, dan tidak sepatutnya mengabaikan pertanyaan tentangnya.
Dia berkata: Semua yang menjadi kewajibannya dari berbagai sebab adalah sama, baik dari tindak pidana, titipan, pelanggaran, mudharabah, atau lainnya. Mereka akan membagi hartanya secara proporsional, kecuali jika salah seorang dari mereka memiliki harta tertentu yang bisa diambil darinya, dan tidak ada yang ikut serta dalam harta itu selain dia. Orang merdeka tidak boleh ditahan karena hutang jika tidak ditemukan hartanya, dan tidak boleh ditahan jika diketahui bahwa dia tidak memiliki apa-apa; karena Allah Azza wa Jalla berfirman: “Dan jika (orang yang berhutang) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan.” (QS. Al-Baqarah: 280). Jika seorang kreditur ditahan, dinyatakan pailit, dan disumpah, kemudian muncul kreditur lain, maka tidak ada penahanan atau sumpah baru kecuali jika dia mendapatkan kelapangan setelah penahanan, maka dia ditahan untuk kreditur kedua dan pertama. Jika dia ditahan, disumpah, dinyatakan pailit, dan dibebaskan, kemudian mendapatkan harta lagi, maka dia boleh melakukan apa saja dengan hartanya, seperti memerdekakan, menjual, menghadiahkan, atau lainnya, sampai penguasa memberlakukan penyitaan baru; karena penyitaan pertama bukanlah penyitaan yang sah karena dia tidak dianggap cakap. Penyitaan itu hanya untuk mencegahnya menguasai hartanya dan membaginya kepada krediturnya. Jadi, apa yang dia dapatkan setelah itu tidak terkena penyitaan.
Jika seseorang dinyatakan pailit dan memiliki barang-barang yang terdeskripsi, aset dari penjualan, pinjaman, tindak pidana, mahar istri, dan lainnya yang menjadi kewajibannya, maka semuanya sama. Para pemilik barang akan membagi sesuai nilainya pada hari kepailitan, dan apa yang mereka dapatkan akan dibelikan barang sesuai syarat mereka. Jika mereka mendapatkan hak mereka sepenuhnya, maka itu sudah cukup. Jika tidak mendapatkan sepenuhnya, atau hanya setengah, kurang, atau lebih, kemudian dia mendapatkan harta lagi, maka para pemilik barang berhak menuntut sisa nilai barang mereka pada kepailitan kedua untuk dibelikan; karena mereka berhak mengambil barang mereka jika menemukan hartanya, atau sebagian jika tidak menemukan semuanya.
[BAB TENTANG PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG KEPAILITAN]
Aku bertanya kepada Abu Abdillah: Apakah ada yang berbeda pendapat denganmu tentang kepailitan? Dia menjawab: Ya, sebagian orang berbeda pendapat dengan kami tentang kepailitan.
Dia mengklaim bahwa jika seorang laki-laki menjual barang kepada laki-laki lain secara tunai atau dengan tempo, dan pembeli menerima barang tersebut, kemudian pembeli bangkrut sementara barang itu masih utuh, maka barang tersebut menjadi harta milik pembeli, dan penjual serta kreditur lainnya memiliki hak yang sama. Aku bertanya kepada Abu Abdillah, “Apa dalil yang mereka gunakan?” Dia menjawab, “Salah seorang dari mereka berkata kepadaku, ‘Bagaimana pendapatmu jika seorang laki-laki menjual seorang budak perempuan dan menyerahkannya kepada pembeli, bukankah pembeli telah memilikinya secara sah sehingga halal baginya untuk menikaminya?’ Aku menjawab, ‘Ya.’ Dia berkata, ‘Bagaimana jika dia menikaminya lalu budak itu melahirkan anak darinya, atau dia menjualnya, memerdekakannya, atau menyedekahkannya, kemudian dia bangkrut, apakah engkau akan menarik kembali sesuatu dari ini dan mengembalikannya sebagai budak?’ Aku menjawab, ‘Tidak.’ Dia berkata, ‘Karena dia telah memilikinya secara sah.’
Aku berkata, ‘Ya.’ Dia bertanya, ‘Lalu bagaimana engkau membatalkan kepemilikan yang sah?’ Aku menjawab, ‘Aku membatalkannya dengan sesuatu yang tidak seharusnya bagiku, bagimu, atau bagi seorang muslim yang mengetahuinya, kecuali jika ada yang membatalkannya untuknya.’ Dia bertanya, ‘Apa itu?’ Aku menjawab, ‘Sunnah Rasulullah ﷺ.’ Dia berkata, ‘Bagaimana jika aku tidak menerima riwayat yang engkau sampaikan?’ Aku menjawab, ‘Kalau begitu, engkau berada dalam posisi kebodohan atau pembangkangan.’ Dia berkata, ‘Itu hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah sendirian.’
Aku berkata, ‘Kami tidak mengetahui riwayat tentang hal itu dari Nabi ﷺ kecuali dari Abu Hurairah saja, dan itu sudah cukup sebagai bukti untuk menetapkan sunnah.’ Dia bertanya, ‘Apakah engkau menemukan bahwa orang-orang menerima riwayat dari Abu Hurairah yang tidak diriwayatkan oleh orang lain, atau dari selainnya?’ Aku menjawab, ‘Ya.’ Dia bertanya, ‘Di mana itu?’ Aku berkata, ‘Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Seorang wanita tidak boleh dinikahi bersama bibinya (dari pihak ayah atau ibu).” Kami dan engkau menerima hadis ini, padahal tidak ada seorang pun yang meriwayatkannya dari Nabi ﷺ selain dia.’ Dia berkata, ‘Benar, tetapi orang-orang telah sepakat tentangnya.’
Aku berkata, ‘Itu justru lebih mewajibkan hujjah atasmu, bahwa orang-orang sepakat menerima hadis Abu Hurairah sendirian tanpa meragukannya, karena Allah ﷻ berfirman, “Diharamkan atas kamu ibu-ibumu…” (QS. An-Nisa: 23) dan firman-Nya, “Dan dihalalkan bagimu apa yang selain itu…” (QS. An-Nisa: 24).’
Aku juga berkata kepadanya, ‘Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Jika anjing menjilat bejana salah seorang dari kalian, cucilah tujuh kali.” Kami menerima seluruh hadisnya, dan engkau juga menerimanya secara keseluruhan. Aku berkata, “Anjing menajiskan air sedikit jika menjilatnya,” dan engkau tidak meragukannya meskipun Abu Qatadah meriwayatkan, “Dari Nabi ﷺ tentang kucing bahwa ia tidak menajiskan air.” Padahal kami dan engkau sepakat bahwa kucing tidak halal dimakan, tetapi engkau tidak mengqiyaskan anjing kepadanya sehingga engkau mengatakan anjing tidak menajiskan air dengan jilatannya, padahal hadis itu hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah.’
Dia berkata, ‘Kami menerimanya karena orang-orang menerimanya.’ Aku berkata, ‘Jika mereka menerimanya dalam satu atau beberapa kasus, maka wajib bagimu dan mereka untuk menerima riwayatnya dalam kasus lain. Jika tidak, berarti engkau memilih seenaknya, menerima yang engkau suka dan menolak yang engkau suka.’
Dia berkata, ‘Kami tahu bahwa Abu Hurairah meriwayatkan beberapa hal yang tidak diriwayatkan oleh orang lain, seperti hadis al-musharra’ (penipuan dalam penjualan susu), hadis tentang pekerja, dan lainnya. Apakah engkau tahu riwayat lain yang hanya diriwayatkan oleh satu perawi?’
Aku menjawab, ‘Ya, Abu Sa’id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Tidak ada zakat pada hasil pertanian kurang dari lima wasaq.” Kami, engkau, dan kebanyakan ahli fatwa mengikuti hadis ini, sementara engkau meninggalkan pendapat sahabatmu dan Ibrahim An-Nakha’i yang mengatakan ada zakat pada setiap hasil bumi, sedikit atau banyak. Mereka berdua mungkin berdalil dengan firman Allah ﷻ, “Dan berikanlah haknya pada hari memetik hasilnya.” (QS. Al-An’am: 141), yang tidak menyebut sedikit atau banyak, dan sabda Nabi ﷺ, “Pada yang disirami hujan, sepersepuluh, dan yang disirami dengan pengairan, seperduapuluh.”‘
Dia berkata, ‘Benar.’
Kami juga menyebutkan hadis Abu Tsa’labah Al-Khusyani bahwa Nabi ﷺ melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring, yang tidak diriwayatkan oleh orang lain sepengetahuanku kecuali dari jalur Abu Hurairah, dan itu bukan hadis yang terkenal di kalangan para perawi. Namun, kami dan engkau menerimanya, sementara orang-orang Makkah menyelisihi kami dan berhujjah dengan firman Allah ﷻ, “Katakanlah: ‘Aku tidak menemukan dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya…’” (QS. Al-An’am: 145), dan firman-Nya, “Dan sungguh, Allah telah menjelaskan apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.” (QS. Al-An’am: 119), serta perkataan Aisyah, Ibnu Abbas, dan Ubaid bin Umair.
Kami berpendapat bahwa satu riwayat dapat dijadikan hujjah, dan tidak ada hujjah dalam takwil atau hadis dari selain Nabi ﷺ jika bertentangan dengan hadis Nabi ﷺ.
Dia berkata, ‘Apa yang engkau sebutkan memang seperti itu.’ Aku berkata, ‘Jika seperti ini, mengapa engkau tidak menjadikannya hujjah?’
Dia menjawab, ‘Hujjah kami untuk tidak menerima pendapatmu tentang kebangkrutan hanyalah ini.’ Kami berkata, ‘Engkau tidak memiliki hujjah, karena aku mendapati engkau dan orang lain menerima riwayat semacam ini dalam kasus lain.’
Seorang lain berkata, ‘Kami meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu pendapat yang mirip dengan pendapat kami.’ Kami menjawab, ‘Ini tidak bisa dijadikan hujjah menurut kami dan engkau, karena prinsip kami berdua adalah jika ada sesuatu yang sah dari Nabi ﷺ, maka tidak ada hujjah dari pendapat siapa pun yang bertentangan dengannya.’
Dia berkata, ‘Kalau begitu…’
Kami berkata, “Kami tidak mengetahui Abu Bakar, Umar, atau Utsman—semoga Allah meridhai mereka—pernah memutuskan seperti yang kalian riwayatkan mengenai kepailitan.” Kami juga berkata, “Kalian tidak meriwayatkan bahwa mereka, atau salah satu dari mereka, pernah mengatakan, ‘Tidak ada zakat pada hasil kurang dari lima wasaq,’ ‘Seorang wanita tidak boleh dinikahkan bersama bibinya dari pihak ayah atau ibunya,’ atau pengharaman semua binatang buas yang bertaring.” Maka kami cukupkan dengan hadis dari Nabi ﷺ dalam hal ini.
Kami berkata, “Itu sudah cukup dan tidak memerlukan yang lain. Yang lainnya hanyalah mengikuti dan tidak berarti apa-apa jika sesuai. Jika diperlukan, diikuti; jika bertentangan, ditinggalkan, dan yang diambil adalah sunnah.” Dia menjawab, “Begitulah pendapat kami.” Kami berkata, “Ya, secara umum, tetapi itu tidak cukup dalam perincian.”
Dia berkata, “Aku tidak sendirian dalam hal yang kalian kritik. Banyak orang dari kalanganmu dan lainnya sepakat denganku—mereka mengambil sebagian hadis dan menolak yang lain.” Aku berkata, “Jika kalian memuji mereka dalam hal ini, masukkanlah mereka dalam kesepakatanmu.” Dia menjawab, “Jika begitu, aku harus selektif dalam ilmu.” Aku berkata, “Katakan apa yang kalian mau, karena kalian telah mencela orang yang melakukannya. Maka tinggalkanlah apa yang kalian cela, dan jangan jadikan hal yang tercela sebagai hujah.”
Dia berkata, “Aku ingin bertanya sesuatu.” Aku menjawab, “Tanyalah.” Dia bertanya, “Bagaimana kalian membatalkan kepemilikan yang sah?” Aku balik bertanya, “Apakah pertanyaan ini punya dasar dalam riwayat Nabi ﷺ?” Dia menjawab, “Tidak, tapi aku ingin tahu apakah ada contoh lain selain ini?”
Aku berkata, “Ya. Bagaimana jika ada rumah yang aku jual kepadamu, lalu ada yang menuntut hak syuf’ah? Bukankah pembeli adalah pemilik sah yang boleh menjual, menghibahkan, atau menjadikannya mahar atau sedekah? Dia juga boleh merobohkan atau membangunnya?” Dia menjawab, “Ya.” Aku bertanya lagi, “Lalu jika datang orang yang berhak syuf’ah, dia mengambilnya dari yang memegangnya?” Dia menjawab, “Ya.” Aku berkata, “Apakah itu berarti kepemilikan sah dibatalkan?” Dia menjawab, “Ya, tapi aku membatalkannya berdasarkan sunnah.”
Aku berkata lagi, “Bagaimana jika seorang lelaki memberikan mahar berupa budak perempuan dan ternak kepada istrinya, lalu budak itu melahirkan dan ternak beranak? Jika suami atau istri meninggal sebelum berhubungan, bukankah mahar itu tetap menjadi milik istri? Dia boleh memerdekakan atau menjual budak dan ternak itu, dan kepemilikannya sah dalam semua hal itu?” Dia menjawab, “Benar.” Aku bertanya lagi, “Lalu jika suami menceraikannya sebelum mengambil budak atau ternak itu, dan semuanya masih di tangan istri, apa hukumnya?” Dia menjawab, “Kepemilikan itu batal, dan suami berhak separuh budak dan ternak jika tidak ada anak, atau separuh nilainya jika ada anak, karena itu muncul selama dalam kepemilikannya.”
Kami bertanya, “Lalu bagaimana kepemilikan sah dibatalkan?” Dia menjawab, “Dengan Kitab.” Kami berkata, “Kami tidak melihat celaanmu dalam harta orang pailit kecuali seperti dalam kasus syuf’ah dan mahar, atau bahkan lebih.” Dia berkata, “Hujahku adalah Kitab atau sunnah.” Kami menjawab, “Begitu pula hujah kami dalam harta orang pailit adalah sunnah, lalu mengapa kalian menyelisihinya?”
Aku berkata kepada Syafi’i, “Kami sepakat denganmu dalam harta orang pailit jika masih hidup, tapi berbeda pendapat jika dia meninggal. Hujah kami adalah hadis Ibnu Syihab yang telah kau dengar.”
(Syafi’i berkata), “Dalam apa yang kami baca dari Malik, Ibnu Syihab meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Siapa yang menjual barang, lalu pembelinya bangkrut sebelum penjual menerima pembayaran, dan penjual menemukan barang itu masih utuh, dia lebih berhak atasnya. Jika pembeli meninggal, penjual barang sama dengan kreditor lainnya.’”
Lalu dia bertanya kepadaku, “Mengapa kalian tidak mengambil hadis ini?” Aku menjawab, “Karena ia mursal. Orang yang menyelisihi kami—seperti yang kau sebutkan—juga menolaknya, meskipun sebenarnya tidak ada alasan baginya untuk menyelisihinya, karena dia menolak hadis dan berpendapat lain. Sedangkan kalian menetapkan hadis, tapi dalam perincian, kalian menyelisihi sebagian dan mengikuti sebagian.”
Dia bertanya lagi, “Lalu mengapa tidak mengambil hadis Ibnu Syihab?” Aku menjawab, “Yang aku ambil lebih utama, karena hadis yang kau pegang itu muttashil, di mana Nabi ﷺ menggabungkan antara kematian dan kepailitan. Sedangkan hadis Ibnu Syihab terputus. Sekalipun tidak ada yang menyelisihinya, ahli hadis tidak akan menetapkannya. Seandainya tidak ada alasan lain untuk meninggalkannya kecuali ini saja, sudah sepantasnya bagi yang paham hadis untuk meninggalkannya dari dua sisi. Selain itu, Abu Bakar bin Abdurrahman meriwayatkan dari Abu Hurairah sebuah hadis yang tidak menyebutkan apa yang diriwayatkan Ibnu Syihab secara mursal. Jika dia meriwayatkan semuanya, aku tidak tahu dari siapa dia meriwayatkan. Bisa jadi dia meriwayatkan awal hadis dan mengakhirinya dengan pendapatnya sendiri.”
(Syafi’i berkata), “Dalam hadis Abu Bakar dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ disebutkan, ‘…maka dia lebih berhak atasnya.’ Ini lebih mirip jika tambahan setelahnya adalah pendapat Abu Bakar, bukan riwayat. Padahal dalam sunnah Nabi ﷺ, jika seseorang menjual barang kepada orang lain, pembeli menjadi pemilik sah yang boleh melakukan apa saja seperti pemilik harta lainnya—memperbudak, menjual, atau memerdekakan budak, meskipun belum menerima pembayaran.”
Harga barang tersebut. Jika pembeli bangkrut dan barang masih berada di tangan pembeli, penjual berhak membatalkan akad jual beli. Begitu pula, pihak yang memiliki hak syuf’ah boleh mengambil syuf’ah, meskipun pembelian itu sah. Jika pembeli yang memiliki barang dengan hak syuf’ah meninggal, maka pihak yang berhak syuf’ah boleh mengambilnya dari ahli warisnya, sebagaimana ia berhak mengambil dari tangan pembeli itu sendiri. Lalu, mengapa hal ini tidak berlaku bagi orang yang menemukan barang miliknya pada orang yang bangkrut, meskipun pemilik asli telah meninggal? Sebagaimana hak penjual tetap berlaku selama pemilik hidup, dan sebagaimana kami katakan dalam syuf’ah.
Bagaimana mungkin ahli waris mewarisi hak untuk menahan barang dari almarhum, padahal mereka hanya mewarisi dari almarhum? Almarhum sendiri tidak memiliki hak untuk mencegah penjual membatalkan transaksi jika harga barang belum dibayar lunas. Dengan demikian, ahli waris hanya mewarisi hak yang dimiliki almarhum atau bahkan kurang dari itu. Namun, kalian justru memberikan hak lebih kepada ahli waris dibandingkan pewaris mereka. Jika perbedaan antara hidup dan mati dianggap sah, seharusnya almarhum lebih berhak untuk mengambil barang miliknya sendiri, karena ia sudah meninggal dan tidak mendapatkan manfaat apa pun, sedangkan orang yang hidup dan bangkrut masih diharapkan bisa membayar utangnya. Kalian justru melemahkan yang kuat dan menguatkan yang lemah, serta mengabaikan sebagian hadis Abu Hurairah dan hanya mengambil sebagian.
Dia (Abu Hurairah) berkata: “Ini bukan termasuk yang kami riwayatkan.” Kami menjawab: “Meskipun kalian tidak meriwayatkannya, hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi terpercaya dari perawi terpercaya lainnya. Ketidakhadiran riwayat kalian tidak melemahkannya, karena banyak hadis yang tidak kalian riwayatkan, tetapi hal itu tidak melemahkannya.”
[Baligh al-Rusyd (Kecakapan Hukum)]
(Imam Syafi’i—rahimahullah—berkata):
Kondisi ketika seorang laki-laki atau perempuan mencapai kecakapan hukum sehingga mereka berhak mengelola harta mereka, Allah Ta’ala berfirman:
“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Jika kalian melihat mereka telah memiliki kecakapan (rusyd), maka serahkanlah harta mereka kepadanya…” (QS. An-Nisa’: 6).
(Imam Syafi’i berkata): Ayat ini menunjukkan bahwa hak pengawasan (hajr) tetap berlaku atas anak yatim hingga mereka memenuhi dua syarat: baligh dan rusyd (kecakapan). Baligh adalah sempurnanya usia 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, kecuali jika laki-laki sudah ihtilam (mimpi basah) atau perempuan sudah haid sebelum usia 15 tahun, maka itu sudah dianggap baligh.
Firman Allah “maka serahkanlah harta mereka kepadanya” menunjukkan bahwa jika mereka telah mencapai baligh dan rusyd, tidak ada seorang pun yang berhak mengelola harta mereka, dan merekalah yang paling berhak atas harta mereka. Mereka boleh melakukan transaksi sebagaimana orang yang sudah lepas dari perwalian. Baik laki-laki maupun perempuan dalam hal ini sama.
Rusyd—wallahu a’lam—adalah kebaikan dalam agama hingga kesaksiannya sah, serta kemampuan mengelola harta dengan baik. Kecakapan mengelola harta diketahui melalui pengujian terhadap anak yatim tersebut. Pengujian ini berbeda tergantung kondisi orang yang diuji.
Jika ia termasuk orang yang aktif di masyarakat, maka kecakapannya bisa dilihat dari interaksinya dalam jual beli sebelum dan sesudah baligh, hingga diketahui bahwa ia menjaga hartanya, menambahnya, dan tidak menyia-nyiakannya untuk hal yang tidak bermanfaat. Pengujian terhadap orang seperti ini lebih mudah.
Namun, jika ia termasuk orang yang dijauhkan dari pasar, maka pengujiannya lebih sulit dibandingkan yang pertama.
(Imam Syafi’i berkata): Kepada orang yang berada di bawah perwalian, diberikan nafkah untuk sebulan. Jika ia bisa mengelolanya dengan baik, membeli kebutuhannya dengan tepat, maka ia diuji dengan pemberian sedikit harta. Jika terlihat ia mampu menjaga dan mengelolanya dengan bijak, maka hartanya diserahkan kepadanya.
Pengujian terhadap perempuan—karena sedikitnya interaksi mereka dalam jual beli—lebih sulit. Perempuan diuji oleh wanita lain atau mahramnya dengan cara yang sama, yaitu dengan memberikan nafkah dan melihat bagaimana ia mengelola pembelian kebutuhan. Jika terlihat kecakapannya dalam mengelola nafkah—seperti yang dijelaskan pada anak laki-laki yang sudah baligh—maka sedikit hartanya diserahkan. Jika ia bisa mengelolanya dengan baik, maka seluruh hartanya diserahkan, baik ia sudah menikah atau belum. Pernikahan tidak menambah atau mengurangi kecakapannya, sebagaimana tidak memengaruhi kecakapan anak laki-laki.
Kurang darinya dan mana saja yang dinikahi sedangkan dia tidak rasyd (belum dewasa akalnya) dan memiliki anak, maka walinya menguasai hartanya; karena syarat Allah -Azza wa Jalla- adalah menyerahkan harta ketika telah menggabungkan antara rasyd dan baligh, sedangkan pernikahan bukan termasuk salah satunya. Dan siapa saja yang berada di bawah perwalian hartanya, maka dia berhak melakukan apa saja dengan hartanya sebagaimana yang dilakukan oleh pemilik harta lainnya, baik itu perempuan maupun laki-laki, baik yang sudah bersuami maupun yang belum. Suami tidak memiliki hak perwalian atas harta istrinya. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama yang saya ketahui bahwa laki-laki dan perempuan, jika masing-masing telah mencapai baligh dan rasyd, maka harta mereka diserahkan kepada mereka secara sama; karena mereka termasuk anak yatim. Jika mereka telah keluar dari perwalian, maka status mereka sama seperti orang lain, di mana masing-masing berhak melakukan apa saja dengan hartanya sebagaimana orang yang tidak berada di bawah perwalian orang lain.
Jika ada yang berkata: “Perempuan yang bersuami berbeda dengan laki-laki, dia tidak boleh memberikan hartanya tanpa izin suaminya,” maka katakanlah kepadanya bahwa Kitabullah -Azza wa Jalla- dalam perintah-Nya untuk menyerahkan harta kepada anak yatim ketika mereka telah mencapai rasyd menunjukkan kebalikan dari apa yang kamu katakan. Karena siapa pun yang telah Allah -Azza wa Jalla- keluarkan dari perwalian, tidak ada seorang pun yang berhak menguasainya kecuali jika terjadi kebodohan atau kerusakan pada dirinya. Demikian pula laki-laki dan perempuan, atau hak seorang Muslim atas harta mereka. Adapun jika tidak demikian, maka laki-laki dan perempuan sama. Jika kamu membedakan antara keduanya, maka kamu harus membawa bukti atas perbedaanmu terhadap dua hal yang disamakan.
Jika ada yang berkata: “Telah diriwayatkan bahwa ‘perempuan tidak boleh memberikan hartanya sedikit pun tanpa izin suaminya’,” maka jawabannya: Kami telah mendengarnya, tetapi riwayat itu tidak kuat sehingga tidak wajib bagi kami untuk mengikutinya. Al-Qur’an menunjukkan kebalikannya, kemudian Sunnah, kemudian atsar, kemudian akal sehat. Jika dia berkata: “Sebutkan ayat Al-Qur’an,” maka kami katakan: Ayat di mana Allah -Azza wa Jalla- memerintahkan untuk menyerahkan harta kepada mereka dan menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Tidak boleh membedakan antara keduanya tanpa dalil yang mengikat.
Jika dia berkata: “Apakah kamu menemukan dalam Al-Qur’an petunjuk selain ini yang mendukung pendapatmu?” Jawabnya: Ya. Allah -Azza wa Jalla- berfirman:
“Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya, padahal kamu telah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (perempuan) memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Dan pemaafan lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan karunia di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 237)
Ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki wajib menyerahkan separuh mahar kepada perempuan, sebagaimana dia wajib menyerahkan hak kepada laki-laki lain yang berhak atasnya. Sunnah juga menunjukkan bahwa perempuan berhak memaafkan (membebaskan) sebagian dari hartanya, dan Allah -Azza wa Jalla- menganjurkan untuk memaafkan serta menyebutkan bahwa hal itu lebih dekat kepada takwa. Dia menyamakan antara perempuan dan laki-laki dalam kebolehan memaafkan hak yang wajib bagi masing-masing.
Allah -Azza wa Jalla- juga berfirman:
“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’: 4)
Dia menjadikan pemberian mahar yang wajib bagi perempuan sebagai hak yang harus diserahkan suami kepada mereka, sebagaimana mereka menyerahkan hak kepada laki-laki lain yang berhak atas mereka. Dan dihalalkan bagi laki-laki untuk mengambil apa yang dengan rela diberikan oleh istrinya, sebagaimana dihalalkan bagi mereka mengambil apa yang dengan rela diberikan oleh orang lain dari harta mereka. Tidak ada perbedaan antara hukum mereka, istri-istri mereka, dan orang lain dalam hal penyerahan hak-hak mereka.
Allah -Azza wa Jalla- juga berfirman:
“Dan jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya.” (QS. An-Nisa’: 20)
Dan firman-Nya:
“Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang pembayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.” (QS. Al-Baqarah: 229)
Dia menghalalkan jika pemberian itu berasal dari perempuan, sebagaimana dihalalkan bagi laki-laki untuk mengambil harta orang lain tanpa batasan sepertiga, lebih sedikit, atau lebih banyak. Dan Dia mengharamkannya jika berasal dari laki-laki, sebagaimana diharamkan merampas harta orang lain.
Allah -Azza wa Jalla- berfirman:
“Dan bagimu (para suami) mendapat separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.” (QS. An-Nisa’: 12)
Dia tidak membedakan antara suami dan istri dalam hal masing-masing berhak berwasiat atas hartanya, dan bahwa hutang masing-masing menjadi tanggungan atas hartanya. Jika demikian, maka perempuan berhak memberikan hartanya kepada…
Dia (perempuan) bertindak tanpa izin suaminya dan berhak menahan maharnya serta memberikannya, tanpa mengurangi sedikit pun. Jika diceraikan, dia berhak mengambil separuh dari apa yang diberikan suaminya, bukan separuh dari apa yang dibeli di bawah nilai mahar tersebut. Jika mahar menjadi haknya, dia boleh menahannya dan semisalnya.
Jika ada yang bertanya: “Di manakah Sunnah dalam hal ini?” Aku (Imam Syafi’i) menjawab: Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa’id dari ‘Amrah binti Abdurrahman, yang mengabarkan kepadanya bahwa Habibah binti Sahl Al-Anshariyah adalah istri Tsabit bin Qais bin Syammas. Suatu ketika, Rasulullah ﷺ keluar untuk shalat Subuh dan menemukan Habibah binti Sahl di depan pintunya saat fajar. Rasulullah ﷺ bertanya, “Siapa ini?” Dia menjawab, “Aku Habibah binti Sahl, wahai Rasulullah.” Beliau bertanya, “Ada apa denganmu?” Dia berkata, “Aku dan Tsabit bin Qais tidak bisa hidup bersama.” Ketika Tsabit bin Qais datang, Rasulullah ﷺ bersabda, “Ini Habibah binti Sahl, dia telah menyampaikan apa yang Allah kehendaki.” Habibah berkata, “Wahai Rasulullah, semua yang dia berikan padaku masih ada padaku.” Rasulullah ﷺ bersabda, “Ambillah darinya.” Maka Tsabit mengambilnya, dan Habibah pun kembali ke keluarganya.
(Imam Syafi’i berkata): Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi’ dari seorang mantan budak Shafiyyah binti Abi Ubaid bahwa dia menebus dirinya dari suaminya dengan segala yang dimilikinya, dan Abdullah bin Umar tidak mengingkarinya.
(Imam Syafi’i berkata): Sunnah ini menunjukkan seperti yang ditunjukkan Al-Qur’an bahwa jika seorang wanita menebus dirinya dari suaminya, halal bagi suaminya untuk mengambil tebusan darinya. Seandainya dia tidak berhak atas hartanya seperti laki-laki yang tidak dibatasi haknya, maka tidak halal baginya untuk menebus diri.
Jika ada yang bertanya: “Di manakah qiyas dan logika dalam hal ini?” Aku menjawab: Jika Allah ﷻ membolehkan suaminya mengambil apa yang diberikannya, ini hanya berlaku bagi yang berhak atas hartanya. Jika hartanya bisa diwariskan dan dia bisa melarang suaminya mengambilnya, maka dia seperti pemilik harta lainnya.
Seandainya ada yang berpendapat berdasarkan hadits yang tidak kuat bahwa dia tidak boleh memberi tanpa izin suaminya kecuali yang diizinkan, maka tidak ada alasan kecuali jika suaminya adalah walinya. Namun, jika seorang laki-laki menjadi wali bagi laki-laki atau perempuan lain, lalu dia memberinya sesuatu, tidak halal baginya mengambilnya, karena pemberiannya sama seperti pemberian kepada orang lain.
Jika dikatakan bahwa suaminya adalah mitra dalam hartanya, maka ditanya: “Apakah mitra separuh?” Jika dia menjawab “Ya,” maka dikatakan: “Berbuatlah dengan separuh lainnya sesukamu, dan suami berbuat dengan separuhnya sesukanya?” Jika dia berkata, “Sedikit atau banyak,” aku katakan: “Tetapkanlah bagian untuknya dari hartanya.” Jika dia berkata, “Hartanya tergadai padanya,” maka ditanya: “Berapa nilai gadainya hingga dia bisa menebusnya?” Jika dia berkata, “Tidak tergadai,” maka dikatakan: “Katakanlah sesukamu, karena suami bukan mitra dalam hartanya, tidak berhak mengambil sedikit pun, hartanya tidak tergadai sehingga bisa ditebus, dan suami bukan walinya.”
Seandainya suaminya adalah walinya tetapi dia boros, maka kami akan mencabut perwaliannya dan menunjuk orang lain. Siapa pun yang keluar dari pendapat-pendapat ini tidak akan menemukan dalil yang bisa diikuti, tidak ada qiyas, dan tidak logis.
Jika seorang wanita boleh memberi sepertiga dari hartanya dan tidak lebih, maka dia tidak dianggap berada di bawah perwalian, suaminya bukan mitra, hartanya tidak tergadai padanya, dia tidak dilarang mengelola hartanya, dan tidak dibiarkan bebas bersamanya. Kemudian, dia diizinkan memberi sepertiga demi sepertiga hingga hartanya habis. Jadi, apa yang menghalanginya dari hartanya?
Jika ada yang berkata, “Dia dinikahi karena kemudahan (hartanya),” maka ditanya: “Bagaimana jika dia menikahi perempuan miskin, lalu kemudian dia kaya? Apakah suami akan membiarkannya dan hartanya?” Jika dia menjawab “Ya,” berarti dia mengeluarkannya dari pembatasan. Jika “Tidak,” berarti dia melarangnya dari apa yang tidak ditipunya.
Atau bagaimana jika dia berkata, “Aku tertipu, maka aku tidak akan membiarkannya mengeluarkan hartanya untuk merugikanku?” Maka ditanya: “Bagaimana jika dia tertipu, misalnya dikatakan perempuan itu cantik, ternyata tidak, atau dikatakan kaya, ternyata miskin? Apakah maharnya dikurangi atau dikembalikan?”
Atau bagaimana jika pendapat ini diterapkan pada perempuan, tetapi jika laki-laki yang kaya menikahi perempuan terhormat, dan dia memberi tahu bahwa dia hanya menikah karena kekayaannya, lalu dia menipunya dan menyedekahkan seluruh hartanya? Jika ini dibolehkan baginya, maka dia telah menzaliminya dengan melarangnya dari hartanya yang dihalalkan untuknya.
Jika dikatakan, “Dia dipaksa membelikan peralatan seperti kebiasaan,” karena ini adalah kebiasaan masyarakat di tempat kami—misalnya, perempuan menyedekahkan seribu dirham tetapi membeli peralatan lebih dari sepuluh ribu, padahal dia miskin dan hanya punya pakaian dan alas tidur—maka kebiasaan masyarakat juga menunjukkan bahwa laki-laki miskin yang terhormat bisa menikahi perempuan kaya, lalu dia berkata, “Dia akan mengelola hartaku.”
Ini adalah pernikahan dan dia membelanjakan dari hartanya, dan hal-hal serupa seperti yang telah dijelaskan, serta hal-hal baik yang biasa dilakukan orang. Hakim berwenang memutuskan berdasarkan yang wajib, bukan yang indah atau yang biasa dilakukan orang.
(Imam Syafi’i berkata): Bukti dapat diterapkan terhadap yang menyelisihi kami dengan lebih dari yang telah dijelaskan, dan dalam hal yang lebih sedikit dari yang dijelaskan pun ada buktinya. Tidak ada pendapat yang benar dalam hal ini kecuali berdasarkan makna Kitabullah -Azza wa Jalla-, Sunnah, atsar, dan qiyas bahwa maharnya adalah harta dari hartanya, dan bahwa jika dia telah baligh, dia berhak mengelola hartanya sebagaimana laki-laki, tanpa perbedaan antara dia dan laki-laki.